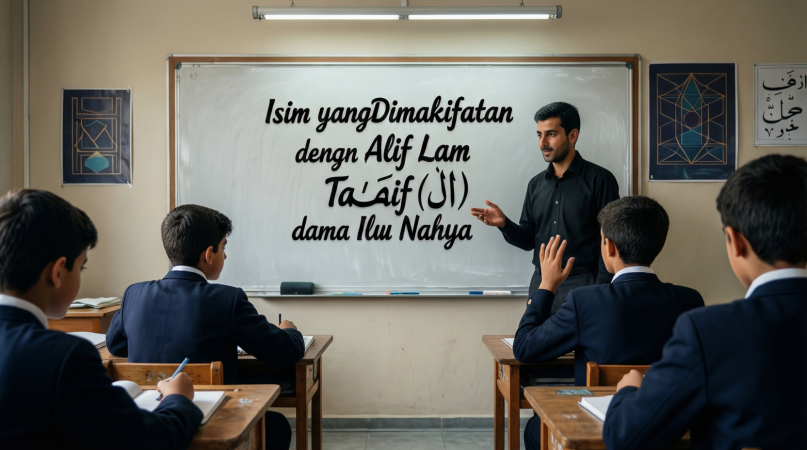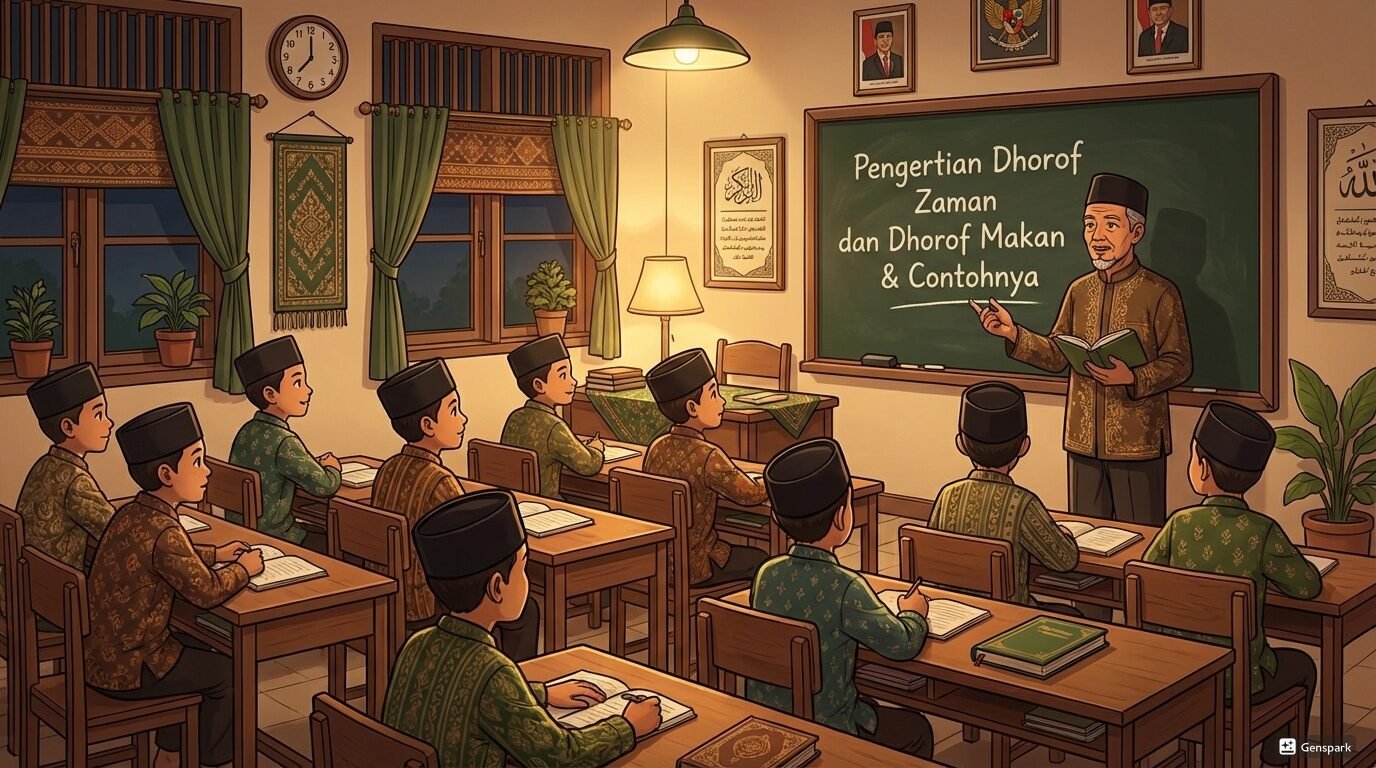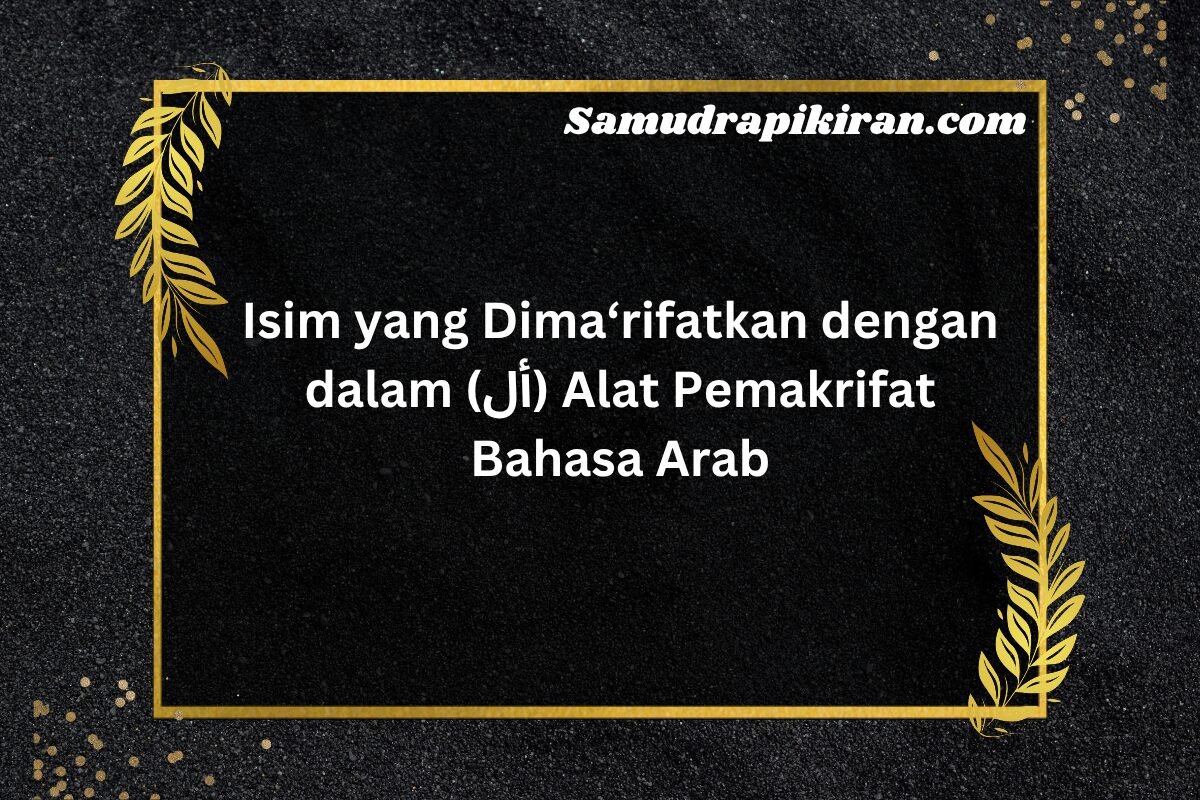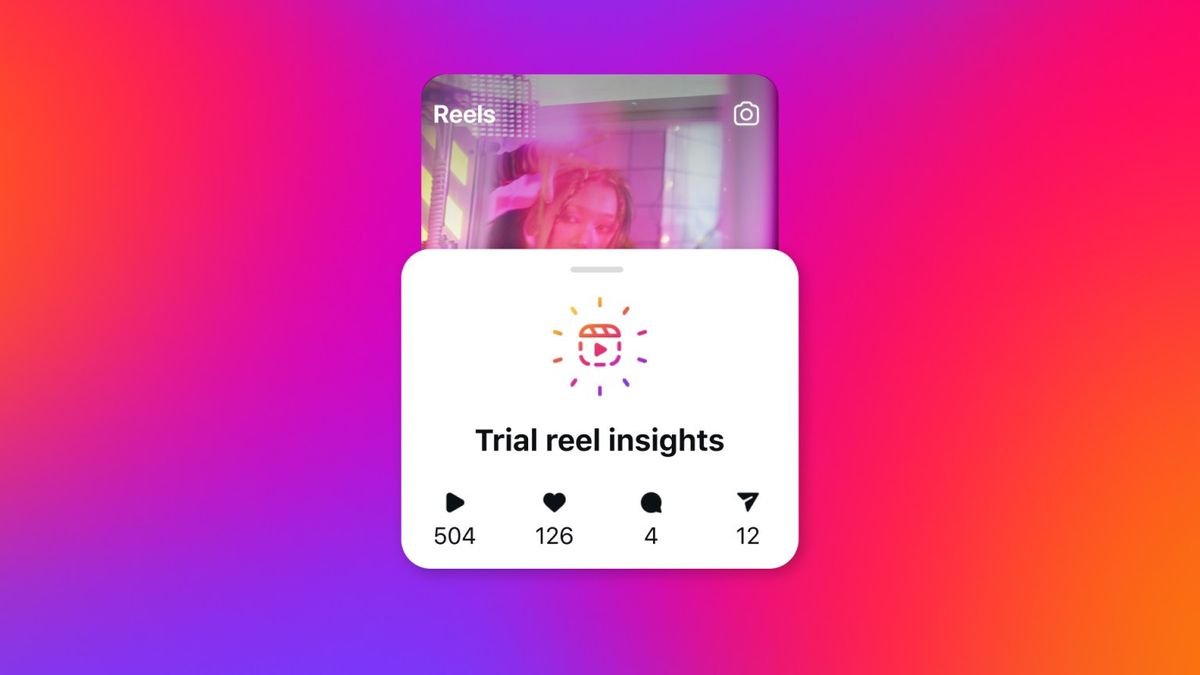Mengenal Konsep Dhorof Zaman dan Dhorof Makan dalam Bahasa Arab dan Contohnya

Samudrapikiran.com – Dalam kajian tata bahasa Arab (nahwu), terdapat satu konsep penting yang sering digunakan untuk menyatakan keterangan waktu dan tempat, yakni dhorof. Meski tampak sederhana, pemahaman terhadap dhorof—baik zaman (waktu) maupun makan (tempat)—memiliki peran strategis dalam membentuk kalimat yang efektif dan sesuai kaidah.
Dalam ilmu nahwu klasik seperti yang diajarkan dalam kitab Alfiyah dan Jurumiyah, dhorof dikenal juga dengan istilah maf’ul fiih, yakni objek yang menjelaskan “di mana” atau “kapan” suatu peristiwa terjadi. Hal ini karena di dalamnya tersimpan makna harfiyah dari kata fii (في) yang berarti “di/dalam”.
Dhorof Zaman: Menunjukkan Waktu Terjadinya Peristiwa
Dhorof zaman digunakan untuk menunjukkan waktu berlangsungnya suatu peristiwa. Secara gramatikal, ia merupakan isim (kata benda) yang dinashabkan karena menjadi tempat terjadinya pekerjaan (fi’il) secara tidak langsung. Kata-kata seperti اليوم (hari ini), غدًا (besok), صباحًا (pagi), atau أبدًا (selamanya) merupakan contoh dhorof zaman.
Contoh dalam kalimat:
سافرتُ غدًا إلى مكة
(Saya bepergian besok ke Mekkah)
Kata غدًا (besok) adalah dhorof zaman karena menunjukkan waktu dari peristiwa bepergian.
Dhorof Makan: Menunjukkan Lokasi Terjadinya Peristiwa
Sementara itu, dhorof makan merujuk pada tempat terjadinya sebuah peristiwa. Seperti halnya dhorof zaman, ia juga merupakan isim yang dinashabkan karena menjadi “wadah” terjadinya fi’il, dengan takdir makna fii.
Contoh dhorof makan antara lain: أمام (di depan), تحت (di bawah), وراء (di belakang), dan بين (di antara).
Contoh dalam kalimat:
جلستُ أمامَ المعلم
(Saya duduk di depan guru)
Kata أمامَ menunjukkan posisi tempat, dan dengan demikian termasuk dhorof makan.
Kapan Sebuah Isim Tidak Dapat Disebut Dhorof?
Tidak semua isim yang berkaitan dengan waktu atau tempat dapat disebut dhorof. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah kata masuk dalam kategori ini:
- Isim tersebut tidak menjadi mubtada atau khabar.
Contoh:
مجلسك مجلسٌ حسنٌ
(Majlismu adalah majlis yang baik)
Di sini مجلس adalah mubtada dan khabar, bukan dhorof.
- Isim tersebut tidak dalam bentuk majrur (berharokat jer).
Contoh:
جلستُ في مجلسك
(Saya duduk di majlismu)
Karena memakai huruf fi, maka tidak disebut dhorof.
- Isim tersebut berfungsi sebagai maf’ul biasa.
Contoh:
علمتُ مجلسَك
(Saya mengetahui majlismu)
Kata مجلسك adalah objek langsung, bukan dhorof.
- Tidak mengandung makna tempat/waktu secara tetap.
Contoh:
ذهبتُ مكة
(Saya pergi ke Mekkah)
Meskipun مكة menunjukkan tempat, ia bukan dhorof karena tidak selalu bermakna fii.
Siapa yang Menyebabkan Dhorof Dinashabkan?
Dalam struktur kalimat Arab, terdapat istilah amil, yakni unsur yang menyebabkan perubahan bentuk akhir kata (i’rab). Dhorof bisa dinashabkan oleh:
- Fi’il (kata kerja)
رأيتُ زيدًا يومَ الجمعة
(Saya melihat Zaid pada hari Jumat)
- Masdar (kata dasar)
عجبتُ من نظري زيدًا يومَ الجمعة
(Aku kagum terhadap penglihatanku pada Zaid hari Jumat)
- Sifat (isim sifat)
أنا ناظرٌ زيدًا يومَ الجمعة
(Aku sedang memperhatikan Zaid hari Jumat)
Dalam beberapa konteks, amilnya bisa dihilangkan karena kebutuhan struktur kalimat. Misalnya, saat dhorof menjadi keterangan tempat (hal), sifat, atau bagian dari silah mausul (relatif clause).
Kriteria Isim yang Bisa Dijadikan Dhorof
- Untuk Dhorof Zaman, semua jenis waktu bisa dijadikan dhorof, baik waktu yang tidak spesifik (mubham) seperti لحظة (sejenak), maupun yang dibatasi dengan jumlah (يومين = dua hari) atau sifat (يومًا واحدًا = satu hari saja).
- Untuk Dhorof Makan, hanya kata yang memiliki makna umum (mubham) atau menunjukkan ukuran (seperti meter, mil, dan lainnya) yang dapat berfungsi sebagai dhorof.
Contoh:
سرتُ ثلاثة أميال
(Saya berjalan sejauh tiga mil)
جلستُ مجلسَ زيد
(Saya duduk di tempat duduk Zaid)
Namun, jika isim tempat tersebut tidak berasal dari fi’il, maka harus menggunakan huruf jar:
جلستُ في مرمى زيد
(Saya duduk di tempat sasaran Zaid)
Penutup
Pemahaman terhadap dhorof zaman dan dhorof makan menjadi bagian penting dalam menguasai bahasa Arab secara struktural. Melalui kaidah ini, seseorang dapat mengekspresikan waktu dan tempat secara tepat, sesuai dengan fungsi sintaksis dalam kalimat Arab klasik. Sebagai bagian dari ilmu nahwu, topik ini tidak hanya relevan dalam konteks pembelajaran bahasa, tetapi juga penting dalam memahami teks-teks keagamaan, sastra Arab, dan komunikasi formal berbahasa Arab.